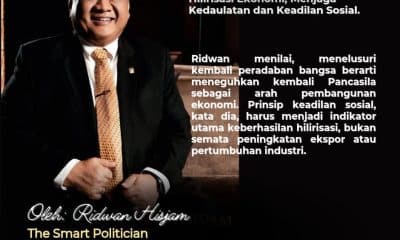Opini
Problematika SKTM dan Layanan Kesehatan Jauh dari Harapan

TULUNGAGUNG– Munculnya kebijakan pemerintah mengenai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis seharusnya menjadi langkah positif untuk menjamin akses kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Namun, banyaknya kendala dan problematika yang terjadi dalam implementasinya menunjukkan bahwa kebijakan ini masih jauh dari harapan dan perlu dievaluasi dengan serius.
Salah satu masalah utama yang muncul adalah prosedur pengajuan SKTM yang terkesan rumit dan berbelit-belit.
Masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil dan kurang mendapatkan pendidikan, sering kali sulit untuk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.
Akibatnya, banyak orang yang seharusnya berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis justru terhambat oleh administrasi yang tidak efisien.
Ini menciptakan diskriminasi tidak hanya dalam akses kesehatan, tetapi juga merusak esensi dari bantuan sosial itu sendiri.
Selain itu, ada isu tentang ketidakakuratan data yang seringkali dijadikan dasar dalam penerbitan SKTM. Banyak warga yang terdaftar sebagai penerima program ini bukanlah yang paling membutuhkan, sementara mereka yang benar-benar berada dalam keterbatasan sering kali terlewatkan.
Data yang tidak akurat menjadi batu sandungan bagi upaya pemerintah untuk menjangkau masyarakat secara efektif.
Seharusnya, pemerintah melakukan pengkinian dan validasi data secara berkala agar SKTM bisa lebih mencerminkan kondisi nyata masyarakat.
Tak kalah pentingnya adalah kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pemegang SKTM.
Masyarakat sering kali melaporkan bahwa meskipun mereka memiliki SKTM, pelayanan yang mereka terima tidak memadai, baik dari segi waktu tunggu, perhatian tenaga medis, maupun ketersediaan obat-obatan.
Ini menciptakan rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem kesehatan yang seharusnya melindungi mereka.
Jika tujuan dari SKTM adalah untuk menjamin akses terhadap layanan kesehatan, maka seharusnya pemerintah juga memastikan bahwa kualitas pelayanan tersebut tidak tereduksi, terlepas dari status ekonomi individu.
Ada pula masalah stigmatisasi yang dialami oleh pemegang SKTM. Dalam beberapa kasus, mereka yang menggunakan SKTM mendapatkan perlakuan diskriminatif dari petugas maupun masyarakat lainnya.
Ini menimbulkan rasa malu dan menghalangi mereka untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak mereka.
Strategi komunikasi publik yang lebih baik harus diterapkan untuk mendorong kesadaran akan pentingnya SKTM sebagai alat untuk membantu mereka yang sedang kesulitan, bukannya sebagai label negatif.
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah perlu meninjau ulang dan mereformasi sistem SKTM secara menyeluruh.
Pertama, perlu ada simplifikasi proses pengajuan SKTM agar lebih user-friendly dan dapat diakses oleh semua kalangan.
Kedua, pengelolaan data yang lebih baik harus menjadi prioritas utama. Implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan data sosial akan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ketiga, pelatihan bagi tenaga medis dalam memberikan layanan kepada pemegang SKTM juga sangat penting untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.
Akhirnya, perlu ditekankan bahwa SKTM seharusnya bukan sekadar kebijakan administrasi, tetapi merupakan cerminan dari komitmen pemerintah untuk menghormati hak asasi setiap warga negara dalam mendapatkan layanan kesehatan. Kesehatan adalah hak, bukan privilese.
Jika pemerintah ingin menjadikan SKTM sebagai alat untuk mendukung akses kesehatan, maka pembaruan dan penyesuaian kebijakan yang mendasar adalah keharusan.
Hanya dengan cara ini, kita dapat menciptakan sistem layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Penulis : Mashuri, seorang Jurnalis dan juga Ketua Ikatan Wartawan Online (IWOI) DPD Tulungagung.
Editor : JK
Opini
Dari Sempalan hingga Partai Baru: Tak Ada yang Berhasil Menggerus PDI-Perjuangan

Jakarta— Pernyataan Ali, Ketua Harian PSI, yang menyentil soal politik “yang tak pernah menghasilkan Presiden” dan mengusik trah Sukarno bukan sekadar manuver verbal.
Ini adalah langkah yang dengan sengaja diarahkan untuk memasuki ceruk merah ruang historis, ideologis, dan emosional yang selama puluhan tahun menjadi rumah besar PDI-Perjuangan.
Untuk memahami respons publik dan arah kontestasi politiknya, perjalanan panjang PDI-P serta kegagalan para rivalnya dalam mengoyak konsistensi ideologis banteng perlu dilihat secara utuh.
1. Menyentuh Sukarnoisme: PSI Bermain di Area Berbahaya.
Ketika Ali menyinggung sejarah politik Megawati dan menyebut kubu “yang tidak pernah melahirkan presiden”, ia sesungguhnya menyentuh nadi terdalam PDI-P: legitimasi historis dan trah Sukarno.
Bagi PDI-P, Sukarnoisme bukan ornamen simbolik. Ia adalah ideologi yang dirawat, diwariskan, dan menjadi identitas kolektif kader hingga akar rumput.
Karena itu, serangan ke wilayah ini terbaca sebagai tantangan langsung terhadap fondasi ideologis banteng.
2. Momentum PSI: Basis Banteng Memang Sedang Cair, Namun Tidak Kosong Nilai.
PSI melihat peluang politik melalui beberapa indikator:
• Kemenangan Prabowo–Gibran di Jawa Tengah, jantung basis PDI-P.
• Kecenderungan pemilih muda terhadap politik populis ala Jokowi–Gibran.
• Fragmentasi politik lokal yang membuka celah baru.
Namun cairnya basis bukan berarti hilangnya fondasi. Ceruk merah bukan sekadar pasar elektoral, melainkan ruang ideologis yang telah mengakar selama lebih dari dua dekade. Banyak yang gagal memahami kedalaman ini.
3. Sempalan Banteng: PNBK dan PDP Runtuh Karena Tanpa Ideologi.
PNBK dan PDP, dua sempalan awal PDI-P pernah mencoba menjadi alternatif. Namun keduanya hilang tanpa jejak politik yang berarti.
Pelajarannya jelas: PDI-P bukan sekadar mesin elektoral; ia adalah kultur.
Tidak cukup mengandalkan simbol merah dan nama besar untuk merebut ceruk Sukarnois.
4. Demokrat Berkuasa 10 Tahun, Tapi Tetap Tak Bisa Menggeser PDI-P.
Jika ada partai yang pernah menjadi penantang serius PDI-P, itu adalah Partai Demokrat pada era SBY (2004–2014).
Dengan kekuasaan penuh dua periode:
• Demokrat memimpin pemerintahan.
• PDI-P berada sebagai oposisi keras.
• Ketegangan SBY–Megawati menjadi dinamika politik nasional.
Namun hasil jangka panjangnya ironis:
• PDI-P tetap kokoh.
• Elektabilitas Demokrat merosot setelah SBY turun.
• PDI-P justru bangkit dan memenangi Pemilu 2014 dan 2019.
Ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara tidak otomatis melemahkan ideologi.
5. Gerindra Menang Pilpres, Tapi Ceruk Banteng Tetap Tak Tersentuh.
Kini Gerindra memegang kursi kepresidenan. Namun polanya kembali sama:
• Gerindra tumbuh bukan dengan menggerus suara PDI-P.
• Basis banteng tetap stabil.
• Dominasi eksekutif tidak serta-merta mengalihkan loyalitas ideologis.
Kemenangan Pilpres bukan kemenangan atas identitas politik.
6. PDI-P: Satu-Satunya Partai yang Konsisten di Era Reformasi.
Inilah faktor pembeda paling fundamental.
Sejak 1999, PDI-P adalah satu-satunya partai yang:
• Pernah menang, kalah, lalu menang kembali.
• Bertahan sebagai oposisi tanpa kehilangan basis.
• Bangkit dari konflik internal besar.
• Memiliki struktur masif yang teruji puluhan tahun.
• Menjaga kontinuitas ideologi Sukarnoisme lintas tiga generasi pemilih.
Di tengah turbulensi reformasi, hanya PDI-P yang mampu membangun tradisi politik yang konsisten, bukan sekadar mengikuti arus kekuasaan.
Kunci utamanya: Kepemimpinan Megawati yang tegas menjaga ideologi, disiplin organisasi, dan kesinambungan sejarah partai.
Partai lain datang dan pergi. PDI-P justru menua, matang, dan bertahan.
7. Kesimpulan: PSI Boleh Ribut, Tetapi Ceruk Merah Memiliki Gerbang Ideologi.
Manuver PSI yang mengusik trah Sukarno memang memancing perhatian, tetapi memasuki ceruk merah bukan pekerjaan retorika. Ia membutuhkan:
• Konsistensi ideologi
• Basis akar rumput yang terjaga
• Struktur organisasi yang solid
• Rekam jejak panjang
• Kepemimpinan yang stabil
PDI-P telah menghadapi:
• Sempalan banteng — tumbang
• Dua rezim kekuasaan — bertahan
• Rival besar seperti Demokrat dan Gerindra — tetap kokoh
• Pergeseran generasi pemilih — tetap relevan
Kini PSI mencoba masuk gelanggang yang sama. Pertanyaannya sederhana namun berat:
Apakah PSI siap menghadapi bukan hanya PDI-P sebagai partai, tetapi PDI-P sebagai tradisi politik?
Atau sejarah kembali berulang, penantang datang dan pergi, sementara banteng tetap berdiri kokoh di jalur ideologinya. (By/Red)
Oleh: Freddy Moses Ulemlem, SH, MH.
Opini
Hari Jadi Tulungagung ke-820: Saatnya Menata Ulang Prioritas Pembangunan Daerah

TULUNGAGUNG – Kabupaten Tulungagung resmi memasuki usia ke-820 tahun, sebuah capaian historis yang mengingatkan betapa panjang perjalanan daerah ini dalam mengarungi dinamika budaya, politik, dan pembangunan.
Peringatan ini seharusnya tidak berhenti sebagai tradisi seremonial, tetapi menjadi momentum refleksi: bagaimana arah pembangunan Tulungagung akan digagas untuk satu dekade ke depan?
Dikenal sebagai wilayah dengan kekayaan budaya yang kokoh mulai dari peninggalan kerajaan, kesenian jaranan, sampai tradisi agraris Tulungagung memiliki bekal kuat untuk menancapkan identitasnya di tengah perubahan zaman. Namun sekadar merawat budaya tidak lagi cukup.
Dengan potensi wisata pesisir dan seni lokal yang terus hidup, diperlukan langkah strategis untuk menjadikan unsur budaya sebagai penggerak ekonomi.
Pengembangan pariwisata berbasis sejarah, peningkatan kualitas pelaku seni, hingga penyediaan ruang kreatif publik harus masuk dalam prioritas nyata, bukan hanya rencana di atas kertas. Usia ke-820 menjadi waktu tepat untuk melahirkan kebijakan yang mampu menjembatani nilai tradisi dengan kebutuhan generasi modern.
Setahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Tulungagung terlihat cukup pesat: perbaikan jalan, pembenahan fasilitas publik, serta revitalisasi kawasan terus digencarkan.
Meski demikian, pembangunan yang ideal tidak hanya diukur dari seberapa banyak proyek fisik yang berdiri.
Masyarakat kini menunggu hadirnya pembangunan yang menyentuh aspek yang lebih fundamental, seperti:
• Penguatan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal,
• Pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan,
• Penyediaan lapangan pekerjaan berkualitas untuk menekan urbanisasi,
• Digitalisasi layanan publik yang lebih transparan dan mudah diakses.
Warga berharap pembangunan tidak berhenti pada simbol kemajuan, tetapi memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan mereka.
Dengan slogan Hari Jadi ke-820 “Tulungagung Bersatu, Satukan Langkah untuk Tulungagung Maju” serta visi “Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Maju, dan Berakhlak Mulia, Sepanjang Masa”, tahun ini terasa berbeda.
Kepemimpinan baru dengan latar belakang dunia usaha menghadirkan ekspektasi bahwa manajemen pemerintahan akan lebih profesional dan adaptif terhadap perubahan.
Namun ekspektasi membutuhkan pembuktian. Terobosan nyata yang dapat mempercepat lompatan pembangunan harus diwujudkan melalui:
• Inovasi layanan publik,
• Kolaborasi erat dengan UMKM dan sektor usaha,
• Optimalisasi kekuatan desa sebagai motor ekonomi,
• Pengelolaan anggaran yang amanah dan terukur.
Masyarakat kini menanti pemimpin yang bukan hanya berwacana, tetapi mampu menempatkan warga sebagai aktor utama pembangunan.
Usia 820 tahun adalah penanda sejarah, tetapi jauh lebih penting untuk membayangkan bagaimana Tulungagung pada usia 830 tahun mendatang.
Apakah menjadi daerah yang makin kompetitif dan modern, atau tertinggal karena kurang berani mengambil langkah besar?
Di tengah kompetisi antar-kabupaten yang semakin ketat, Tulungagung membutuhkan visi jangka panjang yang bukan hanya kuat di narasi, tapi konsisten dalam pelaksanaan.
Pemerintah, masyarakat, pelaku bisnis, serta komunitas lokal perlu berjalan dalam satu irama untuk mewujudkan daerah yang berdaya saing dan tetap berakar pada budaya.
Peringatan Hari Jadi ke-820 seyogianya menjadi pengingat bahwa perjalanan panjang tidak boleh membuat Tulungagung berpuas diri.
Tantangan ke depan menuntut arah pembangunan yang lebih inklusif, progresif, dan berorientasi pada manusia.
Hanya dengan kesatuan visi dan keberanian mengimplementasikannya, Tulungagung dapat tumbuh menjadi kabupaten yang lebih baik dan membanggakan. Selamat Hari Jadi Tulungagung ke-820. Semoga menjadi momentum kebangkitan baru bagi seluruh masyarakatnya.(DON/Red)
Oleh: Abdul Maliq Hasim, Anggota Banser Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.
Editor: Joko Prasetyo
Opini
Transisi Kepemimpinan Global dalam Geopolitik Energi

Jakarta— Dalam salah satu pidato TED-nya, ilmuwan politik Ian Bremmer mengajukan pertanyaan sederhana tapi tajam “Who runs the world?”
Pertanyaan itu kini sulit dijawab. Dunia yang dulu dipimpin oleh satu kekuatan dominan Amerika Serikat kini berubah menjadi sistem multipolar yang cair.
Kekuasaan tersebar, koordinasi global melemah, dan aliansi lama kehilangan daya rekat.
Bremmer menyebut fenomena ini sebagai dunia G-Zero dunia tanpa pemimpin global yang jelas.
Dalam kondisi seperti ini, politik internasional lebih sering diwarnai oleh kepentingan nasional jangka pendek ketimbang visi kolektif untuk masa depan.
Namun, di balik gejolak politik ini, terdapat satu faktor kunci yang jarang dibicarakan secara mendalam yaitu geopolitik energi.
Energi Sebagai Poros Kekuasaan Dunia.
Menurut Carlos Pascual dan Evie Zambetakis dalam The Geopolitics of Energy (2010), energi bukan sekadar komoditas ekonomi, ia adalah alat kekuasaan.
Negara yang mampu mengendalikan pasokan energi, jalur distribusi, dan teknologi ekstraksi akan memiliki pengaruh politik yang luar biasa.
Contoh paling nyata terlihat dalam ketegangan antara Rusia dan Eropa. Ketergantungan Eropa terhadap gas Rusia selama dua dekade terakhir telah membentuk hubungan politik yang asimetris di mana keputusan energi sering kali menjadi senjata diplomasi.
Pascual menegaskan, “energy security is the new currency of power.” Dalam politik ekonomi global, sumber daya energi kini berfungsi layaknya cadangan devisa geopolitik.
Transisi Energi dan Politik di Asia Timur dan Tenggara.
Namun, dinamika kekuasaan ini mulai bergeser seiring masuknya era transisi energi. Studi oleh Jérémy Jammes, Éric Mottet, dan Frédéric Lasserre (2020) dari Conseil québécois d’Études géopolitiques menunjukkan bahwa Asia Timur dan Asia Tenggara kini menjadi laboratorium besar bagi politik energi baru.
Negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan bersaing dalam investasi teknologi hijau, sementara Indonesia, Vietnam, dan Malaysia bernegosiasi antara ketergantungan pada batu bara dan tekanan global untuk beralih ke energi terbarukan.
Transisi energi ini bukan hanya soal iklim, tapi juga politik ekonomi industrialisasi baru siapa yang akan menguasai rantai pasok lithium, rare earth elements, dan teknologi baterai menjadi pertaruhan strategis abad ke-21.
Mediterania dan Jalur Energi Baru.
Di sisi lain, kawasan Mediterania muncul sebagai pusat energi strategis bagi Eropa. Jalur pipa gas dari Afrika Utara, proyek offshore gas di Laut Tengah, hingga ekspansi terminal LNG menjadikan wilayah ini kunci dalam strategi diversifikasi Eropa.
Keseimbangan baru ini menunjukkan bahwa geopolitik energi kini lebih kompleks, tidak lagi dikontrol oleh segelintir negara produsen, melainkan oleh jaringan ekonomi politik global yang menghubungkan negara, korporasi, dan pasar.
Politik Ekonomi Transisi Antara Pasar dan Kedaulatan.
Dari perspektif politik ekonomi, transisi energi global menggambarkan tarik-menarik antara dua kutub kedaulatan nasional dan mekanisme pasar global.
Negara membutuhkan kebijakan industri strategis untuk menjaga kemandirian energi, namun pada saat yang sama tidak bisa lepas dari tekanan pasar internasional dan investor hijau.
Dalam konteks ini, kebijakan energi bukan hanya soal efisiensi atau emisi karbon, melainkan juga tentang siapa yang mengatur arah akumulasi kapital global. Seperti diingatkan Jammes dkk.
Transisi energi bisa memperkuat ketimpangan baru antara negara produsen bahan baku dan negara penguasa teknologi hijau.
Demokrasi dan Tantangan Kepemimpinan Global.
Ian Bremmer menutup refleksinya dengan peringatan jika dunia tanpa pemimpin, maka tanggung jawab kepemimpinan harus berpindah ke masyarakat global.
Demokrasi hanya bertahan jika warganya sadar akan keterlibatan mereka dalam sistem ekonomi-politik global yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mulai dari harga energi hingga arah investasi publik.
Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, politik energi menjadi cermin politik manusia siapa yang berani berpikir melampaui kepentingan jangka pendek untuk masa depan bersama.
Dunia tidak lagi dikendalikan oleh satu kekuatan tunggal. Namun, kekuasaan baru sedang terbentuk di titik pertemuan antara energi, teknologi, dan ekonomi politik global. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang menguasai dunia, tetapi siapa yang mampu memahami dan mengelola perubahan itu dengan visi jangka panjang.
Referensi.
• Bremmer, Ian. Who Runs the World? (TED Talk, 2022).
• Pascual, Carlos & Zambetakis, Evie. The Geopolitics of Energy. In Energy Security: Economics, Politics, Strategies, and Implications, 2010.
• Jammes, Jérémy; Mottet, Éric; Lasserre, Frédéric. East and Southeast Asian Energy Transition and Politics. Conseil québécois d’Études géopolitiques, 2020. (By/Red)
Oleh: Yuwono Setyo Widagdo, S.Sos., MH.
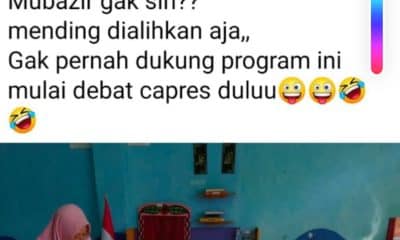
 Redaksi2 minggu ago
Redaksi2 minggu agoViral! Sekdes Ngrance Tulungagung Diduga Nyinyir Soal MBG, Camat Pakel Buka Suara

 Redaksi2 hari ago
Redaksi2 hari agoSekjen Kemenperin Dikabarkan Dilaporkan ke KPK, Aparat Diminta Klarifikasi

 Redaksi2 minggu ago
Redaksi2 minggu agoDigugat ke MK, Pasal 257 KUHP Dinilai Jadi “Senjata” Kriminalisasi Petani Penggarap Lahan Terlantar

 Redaksi1 minggu ago
Redaksi1 minggu agoKasus Dugaan Korupsi Covid-19 dan Jalan Wetar Segera Digelar, Penyidik Panggil Ulang Saksi Gratifikasi

 Redaksi2 minggu ago
Redaksi2 minggu agoKJRA Datangi KSP, Desak Presiden Prabowo Kawal Reforma Agraria Tulungagung–Kediri

 Redaksi6 hari ago
Redaksi6 hari agoSP2HP2 Terbit, Fredi Moses Desak Mabes Polri Ambil Alih Dugaan Korupsi Pulau Wetar: Ada Ancaman dan Isu “Pengamanan Kasus”

 Jawa Timur2 minggu ago
Jawa Timur2 minggu agoSidang Narkotika di PN Tulungagung Memanas, Kuasa Hukum Sebut Terdakwa Tak Pernah Diperiksa

 Redaksi2 minggu ago
Redaksi2 minggu agoBabak Baru Pergolakan Pokmas Tani Mandiri: Dugaan Keterangan Palsu Seret Pelapor Lama ke Ranah Hukum