Opini
Krisis Kepemimpinan, Non Wartawan Kembali Nahkodai Dewan Pers

Jakarta– Awan hitam kembali menyelimuti langit pers nasional. Sederet jurnalis berpengalaman rela membiarkan pers Indonesia dinahkodai figure non wartawan. Dewan Pers Periode 2025 -2028 kini diketuai Komarudin Hidayat, sosok yang tidak memiliki pengalaman di bidang pers.
Bisa dibayangkan jika lembaga profesi pelaut dipimpin seorang ahli bangunan, pasti gak nyambung. Sama halnya dengan pers Indonesia. Lembaga independen Dewan Pers yang mengatur ruang lingkup profesi di bidang pers ini justeru berkali-kali dinahkodai orang yang tidak pernah mengalami pengalaman liputan di tengah panas terik matahari.
“The right man on the right place” atau “orang yang tepat di tempat yang tepat” sepertinya tidak berlaku di institusi pers ini. Padahal sejatinya setiap individu harus ditempatkan pada posisi atau peran yang sesuai dengan kompetensi, kemampuan, keterampilan, dan potensi mereka.
‘Kapal’ Pers Indonesia itu seharusnya dinahkodai wartawan sejati yang berpengalaman dan pernah merasakan suka duka meliput di lapangan. Memahami betapa sulitnya Perusahaan pers memenuhi biayai operasional medianya.
Jika tidak paham cara mengemudikan ‘kapal’ pers Indonesia, bisa-bisa nahkodanya melencengkan arah tujuan dan kapal karam di tengah kerasnya suhu politik dalam negeri dan ancaman geopolitik dunia yang kian memanas.
Kemerdekaan Pers Indonesia Terus Merosot.
Tak heran sejak Dewan Pers dipimpin Ninik Rahayu, sosok yang minim pengalaman di bidang pers, kondisi Pers Indonesia sejak 2022 – 2025 makin terpuruk. Buktinya, pada tahun 2024 lalu, Dewan Pers sendiri mengumumkan secara terbuka bahwa Indeks kemerdekaan pers Indonesia tahun 2023 berada di posisi 71,57 atau menurun cukup tajam dibandingkan IKP tahun 2022 yang mencapai 77,88.
Bahkan IKP Indonesia kembali turun pada tahun 2024 yang hanya pada angka 69,36 atau turun 2,21 poin dibandingkan tahun 2023 di posisi 71,57.
Tak hanya penurunan skor IKP, berdasarkan laporan Reporters Without Borders (RSF) dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia 2024, Indonesia berada di peringkat ke-111 dari 180 negara, yang menandakan penurunan dari tahun 2023 di posisi ke-108.
Dalam Laporan World Press Freedom Index 2025 yang dirilis Reporters Without Borders (RSF) pada 2 Mei 2025, indeks kebebasan pers di Indonesia tercatat kian merosot hingga ke posisi 127 dari 180 negara.
Lebih parah lagi organisasi konstituen Aliansi Jurnalis Independen – AJI merilis hasil studinya pada Maret 2025 yang menunjukkan, 75,1 persen jurnalis di Indonesia pernah mengalami kekerasan, baik fisik maupun digital. Laporan ini didasarkan survei terhadap 2.020 jurnalis di Indonesia.
Kondisi ini tentunya menggambarkan betapa buruknya kehidupan pers Indonesia ketika ditangani orang yang tidak memiliki kompetensi, pengalaman, pengetahuan dan keterampilan di bidang pers.
Legalisasi ‘Pelacuran Pers’ Gunakan Uang Rakyat.
Fenomena buruknya potret kehidupan pers ini diprediksi bakal terus berlanjut. Ketika orang yang tidak berpengalaman di bidang pers dipaksa menahkodai Dewan Pers, lagi-lagi kehidupan pers nasional bakal makin terpuruk.
Lihat saja praktek ‘pelacuran pers’ media kian merajalela di berbagai daerah dan Dewan Pers malah semakin kebablasan membiarkan idealisme pers diobral murah. Pemerintah Daerah pun seolah mendapat durian runtuh untuk ikut melegalkan ‘pelacuran pers’ tersebut agar para pejabat bisa dengan mudahnya mengontrol media, bukan sebaliknya.
Padahal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menyebutkan : “dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independent.”
Artinya Dewan Pers berkewajiban melindungi kemerdekaan pers dengan menyarankan pejabat Pemda melakukan kontrak kerjasama publikasi media melalui tender dengan pihak ketiga. Hal itu penting untuk menempatkan Perusahaan Media menerima orderan melalui pihak ketiga untuk menjaga independensi.
Dengan cara itu wartawan akan sangat bebas menjalankan fungsi kontrol sosial, termasuk meliput dan memberitakan kasus korupsi pejabat tanpa takut dipecat perusahan media karena kontrak kerjasama terancam diputus sepihak.
Sayangnya, bertahun-tahun kondisi ini terus berlangsung. Dampak buruknya, pengawasan pers menjadi sangat minim terhadap kinerja pemerintahan. Tak heran berjejeran kepala daerah terlibat kasus korupsi ditangkap aparat hukum karena bablas mencuri uang rakyat tanpa diawasi pers.
Dan mirisnya seluruh organisasi konstituen Dewan Pers tidak ada yang menentang kebijakan Dewan Pers melegalkan ‘pelacuran pers’ di seluruh Indonesia, malahan kelompok konstituen ini menarik keuntungan dari proyek pencitraan pejabat koruptor menggunakan uang rakyat.
Gerombolan perusak kemerdekaan pers ini justeru menikmati privilege atau hak Istimewa sebagai kakitangan Dewan Pers. Karpet merah digelar khusus untuk anggotanya para konstituen Dewan Pers di berbagai daerah, menikmati uang rakyat demi kepentingan pribadi dan pencitraan pejabat koruptor.
Nasib 47 Ribu Media Pers
Dewan Pers pada tahun 2020 memperkirakan jumlah media pers sebanyak 47.000 yang terdiri dari 43.300 media daring, 2.000 media cetak, 674 media radio, dan 523 media televisi. Sejak dirilis tahun 2020, faktanya tahun 2025 ini, Dewan Pers mencatat dalam situs resminya hanya 1156 media pers yang didata dengan menggunakan istilah terverifikasi faktual dan terverifikasi administrasi.
Kondisi ini dari sisi peningkatan kuantitas tentunya sangat bertentangan dengan tujuan dibentuknya Dewan Pers sebagaimana dijelaskan dalam lembar penjelasan atas UU Pers. Disebutkan : Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.
Faktanya data peningkatan kuantitas media di Dewan Pers justeru sangat minim karena hanya 1156 media pers yang dinyatakan terverifikasi DP dari total sekitar 47 ribu media.
Eks Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu kepada media TEMPO mengklarifikasi bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada waktu lahir tidak mengenal pendaftaran bagi perusahaan pers.
Ketika itu Ninik mengatakan, pendataan perusahaan pers merupakan stelsel pasif dan mandiri. Artinya, perusahaan pers yang berinisiatif untuk mengajukan diri agar diverifikasi (didata) oleh Dewan Pers sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan DP/I/2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers.
Mengacu dari keterangan Ninik ini, bagaimana mungkin Dewan Pers mendorong Pemda membuat regulasi Kerjasama Media dengan Perusahaan yang terverifikasi, padahal pendataan Perusahaan merupakan stelsel pasif dan mandiri. Hal ini tentunya barakibat terjadi diskriminasi terhadap puluhah ribu perusahaan media yang belum mengikuti pendataan verifikasi di Dewan Pers.
Selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini, hampir tidak ada terobosan yang dilakukan Dewan Pers untuk meningkatkan kuantitas pers nasional. Kondisi kehidupan pers nasional justeru makin terpuruk.
Lihat saja berbagai media nasional merilis berita bahwa industri media di Indonesia sedang berada di ujung tanduk. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terus melanda berbagai perusahaan media nasional, termasuk platform digital, seiring dengan penutupan sejumlah media besar di Indonesia, salah satunya adalah media GATRA.
Marjinalisasi pers di Indonesia.
Persoalan lain sektor pers adalah belanja iklan nasional yang mencapai angka fantastis ratusan triliun rupiah pertahun ternyata tidak terdistribusi merata ke seluruh daerah. Semua hanya terpusat di Jakarta.
Lebih miris lagi, angka belanja iklan ratusan triliun rupiah itu hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha media nasional berdomisili di Jakarta. Dengan alsan bisnis, produsen pengguna jasa periklanan hanya diarahkan beriklan di media nasional di Jakarta.
Perusahaan Pers lokal tidak diberi akses untuk bisa ikut menikmati belanja iklan nasional. Media mainstream atau media arus utama nasional justeru dibiarkan memonopoli iklan selama puluhan tahun.
Tak ada satu pun upaya dari Dewan Pers memperjuangkan triliunan rupiah belanja iklan nasional tersebut terdistribusi ke Perusahaan Pers lokal. Pihak Pemerintah Pusat pun turut membiarkan terjadinya Marjinalisasi pers di Indonesia.
Media lokal malahan dipaksa ‘melacurkan’ diri bekerjasama dengan Pemerintah Daerah meski dengan nilai kontrak yang sangat minim. Sementara iklan komersil produk dagang di daerah hanya ditempatkan di media nasional.
Kesejahteraan Pers Terabaikan.
Maraknya pendirian perusahaan pers berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), belum disentuh kebijakan pemerintah. Pers sejatinya memang harus independent. Namun perusahaan pers tetap harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan.
Pemerintah telah membuat regulasi bahwa setiap Perusahaan wajib membayar gaji karyawan dengan standar UMR (Upah Minimum Regional). Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003 yang direvisi melalui UU Cipta Kerja) melarang pengusaha membayar upah di bawah UMR.
PT yang tidak membayar gaji sesuai UMR (Upah Minimum Regional) atau UMP (Upah Minimum Provinsi) dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau denda. Sanksi ini diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, seperti Pasal 185 UU Ketenagakerjaan yang diubah oleh UU Cipta Kerja.
Sanksi Pidananya, perusahaan dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun. Selain pidana penjara, perusahaan juga dapat dikenakan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta. Kemudian Sanksi Administratif, yakni denda administrative maksimal Rp1 juta atau kurungan hingga 3 bulan.
Namun pada kenyataannya, hampir sebagian besar perusahaan media tidak menggaji wartawannya. Kalau pun digaji, banyak wartawan yang nenerima di bawah UMR.
Kondisi ini tentunya sangat mengancam kemerdekaan pers. Wartawan yang tidak sejahtera cenderung gampang menjual idealismenya. Sudah menjadi rahasia umum, tak terkecuali media mainstream, wartawannya rata-rata masih menerima imblan amplop berisi uang dari nara sumber.
Fakta ini tidak bisa dipungkiri karena belum mampu menjamin kesejahteraan wartawan.
Pada akhir tulisan ini, pada prinsipnya penulis tetap menolak mekanisme hasil pemilihan Anggota Dewan Pers termasuk SK Penetapan oleh Presiden, karena bertentangan dengan UU Pers dan berpotensi melanggar hak konstitusional dan hak asazi manusia terhadap pimpinan dan pengurus organisasi pers non konstituen Dewan Pers.
Sebagai penutup penulis menitip asa kepada para Anggota Dewan Pers yang baru untuk berpihak pada media kecil dan wartawan lokal yang termarjinalisasi. Integritas dan ketokohan Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat memang tidak diragukan di bidang pendidikan.
Jika tetap ingin bertahan di Dewan Pers, kemampuan menangani kehidupan pers nasional perlu dibuktikan dengan memahami ketentuan yang diatur dalam UU Pers. (Red)
Oleh : Hence Mandagi – Ketua Umum DPP SPRI.
Opini
Dari Sempalan hingga Partai Baru: Tak Ada yang Berhasil Menggerus PDI-Perjuangan

Jakarta— Pernyataan Ali, Ketua Harian PSI, yang menyentil soal politik “yang tak pernah menghasilkan Presiden” dan mengusik trah Sukarno bukan sekadar manuver verbal.
Ini adalah langkah yang dengan sengaja diarahkan untuk memasuki ceruk merah ruang historis, ideologis, dan emosional yang selama puluhan tahun menjadi rumah besar PDI-Perjuangan.
Untuk memahami respons publik dan arah kontestasi politiknya, perjalanan panjang PDI-P serta kegagalan para rivalnya dalam mengoyak konsistensi ideologis banteng perlu dilihat secara utuh.
1. Menyentuh Sukarnoisme: PSI Bermain di Area Berbahaya.
Ketika Ali menyinggung sejarah politik Megawati dan menyebut kubu “yang tidak pernah melahirkan presiden”, ia sesungguhnya menyentuh nadi terdalam PDI-P: legitimasi historis dan trah Sukarno.
Bagi PDI-P, Sukarnoisme bukan ornamen simbolik. Ia adalah ideologi yang dirawat, diwariskan, dan menjadi identitas kolektif kader hingga akar rumput.
Karena itu, serangan ke wilayah ini terbaca sebagai tantangan langsung terhadap fondasi ideologis banteng.
2. Momentum PSI: Basis Banteng Memang Sedang Cair, Namun Tidak Kosong Nilai.
PSI melihat peluang politik melalui beberapa indikator:
• Kemenangan Prabowo–Gibran di Jawa Tengah, jantung basis PDI-P.
• Kecenderungan pemilih muda terhadap politik populis ala Jokowi–Gibran.
• Fragmentasi politik lokal yang membuka celah baru.
Namun cairnya basis bukan berarti hilangnya fondasi. Ceruk merah bukan sekadar pasar elektoral, melainkan ruang ideologis yang telah mengakar selama lebih dari dua dekade. Banyak yang gagal memahami kedalaman ini.
3. Sempalan Banteng: PNBK dan PDP Runtuh Karena Tanpa Ideologi.
PNBK dan PDP, dua sempalan awal PDI-P pernah mencoba menjadi alternatif. Namun keduanya hilang tanpa jejak politik yang berarti.
Pelajarannya jelas: PDI-P bukan sekadar mesin elektoral; ia adalah kultur.
Tidak cukup mengandalkan simbol merah dan nama besar untuk merebut ceruk Sukarnois.
4. Demokrat Berkuasa 10 Tahun, Tapi Tetap Tak Bisa Menggeser PDI-P.
Jika ada partai yang pernah menjadi penantang serius PDI-P, itu adalah Partai Demokrat pada era SBY (2004–2014).
Dengan kekuasaan penuh dua periode:
• Demokrat memimpin pemerintahan.
• PDI-P berada sebagai oposisi keras.
• Ketegangan SBY–Megawati menjadi dinamika politik nasional.
Namun hasil jangka panjangnya ironis:
• PDI-P tetap kokoh.
• Elektabilitas Demokrat merosot setelah SBY turun.
• PDI-P justru bangkit dan memenangi Pemilu 2014 dan 2019.
Ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara tidak otomatis melemahkan ideologi.
5. Gerindra Menang Pilpres, Tapi Ceruk Banteng Tetap Tak Tersentuh.
Kini Gerindra memegang kursi kepresidenan. Namun polanya kembali sama:
• Gerindra tumbuh bukan dengan menggerus suara PDI-P.
• Basis banteng tetap stabil.
• Dominasi eksekutif tidak serta-merta mengalihkan loyalitas ideologis.
Kemenangan Pilpres bukan kemenangan atas identitas politik.
6. PDI-P: Satu-Satunya Partai yang Konsisten di Era Reformasi.
Inilah faktor pembeda paling fundamental.
Sejak 1999, PDI-P adalah satu-satunya partai yang:
• Pernah menang, kalah, lalu menang kembali.
• Bertahan sebagai oposisi tanpa kehilangan basis.
• Bangkit dari konflik internal besar.
• Memiliki struktur masif yang teruji puluhan tahun.
• Menjaga kontinuitas ideologi Sukarnoisme lintas tiga generasi pemilih.
Di tengah turbulensi reformasi, hanya PDI-P yang mampu membangun tradisi politik yang konsisten, bukan sekadar mengikuti arus kekuasaan.
Kunci utamanya: Kepemimpinan Megawati yang tegas menjaga ideologi, disiplin organisasi, dan kesinambungan sejarah partai.
Partai lain datang dan pergi. PDI-P justru menua, matang, dan bertahan.
7. Kesimpulan: PSI Boleh Ribut, Tetapi Ceruk Merah Memiliki Gerbang Ideologi.
Manuver PSI yang mengusik trah Sukarno memang memancing perhatian, tetapi memasuki ceruk merah bukan pekerjaan retorika. Ia membutuhkan:
• Konsistensi ideologi
• Basis akar rumput yang terjaga
• Struktur organisasi yang solid
• Rekam jejak panjang
• Kepemimpinan yang stabil
PDI-P telah menghadapi:
• Sempalan banteng — tumbang
• Dua rezim kekuasaan — bertahan
• Rival besar seperti Demokrat dan Gerindra — tetap kokoh
• Pergeseran generasi pemilih — tetap relevan
Kini PSI mencoba masuk gelanggang yang sama. Pertanyaannya sederhana namun berat:
Apakah PSI siap menghadapi bukan hanya PDI-P sebagai partai, tetapi PDI-P sebagai tradisi politik?
Atau sejarah kembali berulang, penantang datang dan pergi, sementara banteng tetap berdiri kokoh di jalur ideologinya. (By/Red)
Oleh: Freddy Moses Ulemlem, SH, MH.
Opini
Hari Jadi Tulungagung ke-820: Saatnya Menata Ulang Prioritas Pembangunan Daerah

TULUNGAGUNG – Kabupaten Tulungagung resmi memasuki usia ke-820 tahun, sebuah capaian historis yang mengingatkan betapa panjang perjalanan daerah ini dalam mengarungi dinamika budaya, politik, dan pembangunan.
Peringatan ini seharusnya tidak berhenti sebagai tradisi seremonial, tetapi menjadi momentum refleksi: bagaimana arah pembangunan Tulungagung akan digagas untuk satu dekade ke depan?
Dikenal sebagai wilayah dengan kekayaan budaya yang kokoh mulai dari peninggalan kerajaan, kesenian jaranan, sampai tradisi agraris Tulungagung memiliki bekal kuat untuk menancapkan identitasnya di tengah perubahan zaman. Namun sekadar merawat budaya tidak lagi cukup.
Dengan potensi wisata pesisir dan seni lokal yang terus hidup, diperlukan langkah strategis untuk menjadikan unsur budaya sebagai penggerak ekonomi.
Pengembangan pariwisata berbasis sejarah, peningkatan kualitas pelaku seni, hingga penyediaan ruang kreatif publik harus masuk dalam prioritas nyata, bukan hanya rencana di atas kertas. Usia ke-820 menjadi waktu tepat untuk melahirkan kebijakan yang mampu menjembatani nilai tradisi dengan kebutuhan generasi modern.
Setahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Tulungagung terlihat cukup pesat: perbaikan jalan, pembenahan fasilitas publik, serta revitalisasi kawasan terus digencarkan.
Meski demikian, pembangunan yang ideal tidak hanya diukur dari seberapa banyak proyek fisik yang berdiri.
Masyarakat kini menunggu hadirnya pembangunan yang menyentuh aspek yang lebih fundamental, seperti:
• Penguatan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal,
• Pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan,
• Penyediaan lapangan pekerjaan berkualitas untuk menekan urbanisasi,
• Digitalisasi layanan publik yang lebih transparan dan mudah diakses.
Warga berharap pembangunan tidak berhenti pada simbol kemajuan, tetapi memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan mereka.
Dengan slogan Hari Jadi ke-820 “Tulungagung Bersatu, Satukan Langkah untuk Tulungagung Maju” serta visi “Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Maju, dan Berakhlak Mulia, Sepanjang Masa”, tahun ini terasa berbeda.
Kepemimpinan baru dengan latar belakang dunia usaha menghadirkan ekspektasi bahwa manajemen pemerintahan akan lebih profesional dan adaptif terhadap perubahan.
Namun ekspektasi membutuhkan pembuktian. Terobosan nyata yang dapat mempercepat lompatan pembangunan harus diwujudkan melalui:
• Inovasi layanan publik,
• Kolaborasi erat dengan UMKM dan sektor usaha,
• Optimalisasi kekuatan desa sebagai motor ekonomi,
• Pengelolaan anggaran yang amanah dan terukur.
Masyarakat kini menanti pemimpin yang bukan hanya berwacana, tetapi mampu menempatkan warga sebagai aktor utama pembangunan.
Usia 820 tahun adalah penanda sejarah, tetapi jauh lebih penting untuk membayangkan bagaimana Tulungagung pada usia 830 tahun mendatang.
Apakah menjadi daerah yang makin kompetitif dan modern, atau tertinggal karena kurang berani mengambil langkah besar?
Di tengah kompetisi antar-kabupaten yang semakin ketat, Tulungagung membutuhkan visi jangka panjang yang bukan hanya kuat di narasi, tapi konsisten dalam pelaksanaan.
Pemerintah, masyarakat, pelaku bisnis, serta komunitas lokal perlu berjalan dalam satu irama untuk mewujudkan daerah yang berdaya saing dan tetap berakar pada budaya.
Peringatan Hari Jadi ke-820 seyogianya menjadi pengingat bahwa perjalanan panjang tidak boleh membuat Tulungagung berpuas diri.
Tantangan ke depan menuntut arah pembangunan yang lebih inklusif, progresif, dan berorientasi pada manusia.
Hanya dengan kesatuan visi dan keberanian mengimplementasikannya, Tulungagung dapat tumbuh menjadi kabupaten yang lebih baik dan membanggakan. Selamat Hari Jadi Tulungagung ke-820. Semoga menjadi momentum kebangkitan baru bagi seluruh masyarakatnya.(DON/Red)
Oleh: Abdul Maliq Hasim, Anggota Banser Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.
Editor: Joko Prasetyo
Opini
Transisi Kepemimpinan Global dalam Geopolitik Energi

Jakarta— Dalam salah satu pidato TED-nya, ilmuwan politik Ian Bremmer mengajukan pertanyaan sederhana tapi tajam “Who runs the world?”
Pertanyaan itu kini sulit dijawab. Dunia yang dulu dipimpin oleh satu kekuatan dominan Amerika Serikat kini berubah menjadi sistem multipolar yang cair.
Kekuasaan tersebar, koordinasi global melemah, dan aliansi lama kehilangan daya rekat.
Bremmer menyebut fenomena ini sebagai dunia G-Zero dunia tanpa pemimpin global yang jelas.
Dalam kondisi seperti ini, politik internasional lebih sering diwarnai oleh kepentingan nasional jangka pendek ketimbang visi kolektif untuk masa depan.
Namun, di balik gejolak politik ini, terdapat satu faktor kunci yang jarang dibicarakan secara mendalam yaitu geopolitik energi.
Energi Sebagai Poros Kekuasaan Dunia.
Menurut Carlos Pascual dan Evie Zambetakis dalam The Geopolitics of Energy (2010), energi bukan sekadar komoditas ekonomi, ia adalah alat kekuasaan.
Negara yang mampu mengendalikan pasokan energi, jalur distribusi, dan teknologi ekstraksi akan memiliki pengaruh politik yang luar biasa.
Contoh paling nyata terlihat dalam ketegangan antara Rusia dan Eropa. Ketergantungan Eropa terhadap gas Rusia selama dua dekade terakhir telah membentuk hubungan politik yang asimetris di mana keputusan energi sering kali menjadi senjata diplomasi.
Pascual menegaskan, “energy security is the new currency of power.” Dalam politik ekonomi global, sumber daya energi kini berfungsi layaknya cadangan devisa geopolitik.
Transisi Energi dan Politik di Asia Timur dan Tenggara.
Namun, dinamika kekuasaan ini mulai bergeser seiring masuknya era transisi energi. Studi oleh Jérémy Jammes, Éric Mottet, dan Frédéric Lasserre (2020) dari Conseil québécois d’Études géopolitiques menunjukkan bahwa Asia Timur dan Asia Tenggara kini menjadi laboratorium besar bagi politik energi baru.
Negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan bersaing dalam investasi teknologi hijau, sementara Indonesia, Vietnam, dan Malaysia bernegosiasi antara ketergantungan pada batu bara dan tekanan global untuk beralih ke energi terbarukan.
Transisi energi ini bukan hanya soal iklim, tapi juga politik ekonomi industrialisasi baru siapa yang akan menguasai rantai pasok lithium, rare earth elements, dan teknologi baterai menjadi pertaruhan strategis abad ke-21.
Mediterania dan Jalur Energi Baru.
Di sisi lain, kawasan Mediterania muncul sebagai pusat energi strategis bagi Eropa. Jalur pipa gas dari Afrika Utara, proyek offshore gas di Laut Tengah, hingga ekspansi terminal LNG menjadikan wilayah ini kunci dalam strategi diversifikasi Eropa.
Keseimbangan baru ini menunjukkan bahwa geopolitik energi kini lebih kompleks, tidak lagi dikontrol oleh segelintir negara produsen, melainkan oleh jaringan ekonomi politik global yang menghubungkan negara, korporasi, dan pasar.
Politik Ekonomi Transisi Antara Pasar dan Kedaulatan.
Dari perspektif politik ekonomi, transisi energi global menggambarkan tarik-menarik antara dua kutub kedaulatan nasional dan mekanisme pasar global.
Negara membutuhkan kebijakan industri strategis untuk menjaga kemandirian energi, namun pada saat yang sama tidak bisa lepas dari tekanan pasar internasional dan investor hijau.
Dalam konteks ini, kebijakan energi bukan hanya soal efisiensi atau emisi karbon, melainkan juga tentang siapa yang mengatur arah akumulasi kapital global. Seperti diingatkan Jammes dkk.
Transisi energi bisa memperkuat ketimpangan baru antara negara produsen bahan baku dan negara penguasa teknologi hijau.
Demokrasi dan Tantangan Kepemimpinan Global.
Ian Bremmer menutup refleksinya dengan peringatan jika dunia tanpa pemimpin, maka tanggung jawab kepemimpinan harus berpindah ke masyarakat global.
Demokrasi hanya bertahan jika warganya sadar akan keterlibatan mereka dalam sistem ekonomi-politik global yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mulai dari harga energi hingga arah investasi publik.
Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, politik energi menjadi cermin politik manusia siapa yang berani berpikir melampaui kepentingan jangka pendek untuk masa depan bersama.
Dunia tidak lagi dikendalikan oleh satu kekuatan tunggal. Namun, kekuasaan baru sedang terbentuk di titik pertemuan antara energi, teknologi, dan ekonomi politik global. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang menguasai dunia, tetapi siapa yang mampu memahami dan mengelola perubahan itu dengan visi jangka panjang.
Referensi.
• Bremmer, Ian. Who Runs the World? (TED Talk, 2022).
• Pascual, Carlos & Zambetakis, Evie. The Geopolitics of Energy. In Energy Security: Economics, Politics, Strategies, and Implications, 2010.
• Jammes, Jérémy; Mottet, Éric; Lasserre, Frédéric. East and Southeast Asian Energy Transition and Politics. Conseil québécois d’Études géopolitiques, 2020. (By/Red)
Oleh: Yuwono Setyo Widagdo, S.Sos., MH.

 Redaksi1 minggu ago
Redaksi1 minggu agoSekjen Kemenperin Dikabarkan Dilaporkan ke KPK, Aparat Diminta Klarifikasi

 Redaksi12 jam ago
Redaksi12 jam agoProgram MBG di Tulungagung Tercoreng: Gagal Jaga Mutu, Roti Berjamur Dibagikan ke Siswa SDN 4 Kampungdalem

 Redaksi2 hari ago
Redaksi2 hari agoPT Indoco Surabaya Mangkir, Pokmas Tani Mandiri Beri Ultimatum 7 Hari: Dokumen HGU Dipertanyakan, Lahan Terancam Diusulkan Jadi TORA

 Redaksi2 minggu ago
Redaksi2 minggu agoKasus Dugaan Korupsi Covid-19 dan Jalan Wetar Segera Digelar, Penyidik Panggil Ulang Saksi Gratifikasi

 Redaksi2 minggu ago
Redaksi2 minggu agoSP2HP2 Terbit, Fredi Moses Desak Mabes Polri Ambil Alih Dugaan Korupsi Pulau Wetar: Ada Ancaman dan Isu “Pengamanan Kasus”

 Jawa Timur2 minggu ago
Jawa Timur2 minggu agoSetahun GABAH Memimpin, Bupati Gatut Sunu Ajak Semua Tetap Satu Gerbong demi Tulungagung Maju
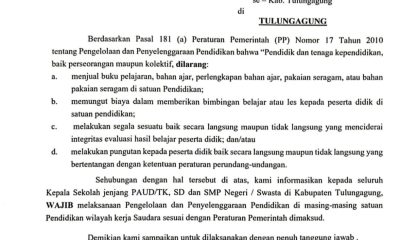
 Redaksi5 hari ago
Redaksi5 hari agoDisdik Tulungagung Pasang Badan untuk Siswa: Jual Beli Baju dan Buku Sekolah Dilarang Keras

 Hukum Kriminal2 minggu ago
Hukum Kriminal2 minggu agoAMKEI Serukan Keadilan: Jangan Lindungi Oknum, Kasus Dugaan Kekerasan Anak di Tual Tak Boleh Berakhir Damai



















